Sesi Berbagi Proses Kreatif Menggarap Karya Multimedia bersama Hafitz Maulana

Rangkaian pelatihan fotografi Permata Photojournalist Grant (PPG) 2020 sampai pada tahap akhir, Selasa, (09/02/2021). Pada pertemuan kali ini, Hafitz Maulana, pewarta foto Tirto.id sekaligus alumni PPG 2019, berbagi mengenai proses kreatifnya selama menggarap karya multimedia. Sebagai informasi, pada pameran foto “Innovation” yang diselenggarakan pada tahun 2020 lalu di galeri Erasmus Huis, Jakarta, Hafitz menyajikan karyanya secara multimedia bertajuk Virtual Insanity: Inside The Life of Pro-Gamer.
Pameran foto karya peserta PPG 2020 rencananya diselenggarakan secara daring. Pada kelas-kelas sebelumnya, peserta memang sudah dibekali pengetahuan teoretis tentang multimedia oleh Saša Kralj. Namun pada sesi kali ini lebih ditujukan untuk berbagi pengalaman teknis saat membuat karya multimedia agar peserta PPG 2020 memperoleh gambaran yang utuh.
“Mungkin hal pertama yang perlu digarisbawahi, pada dasarnya multimedia itu benar-benar lintas medium. Sebetulnya tidak hanya dalam format digital saja ya, tapi bisa dipresentasikan di mana saja dan bentuknya beragam,” tutur Hafitz membuka sesi sharing.
Dalam karyanya tahun lalu, Hafitz bercerita tentang game. Ia menggabungkan foto still dengan audio sehingga menghasilkan efek dan nuansa cerita yang lebih hidup.
“Saya menyebutnya audiophotography, yaitu kombinasi antara dua medium; foto dan audio,” kata Hafitz.
Menurutnya, cara kerja audiophotography mirip seperti film. Hanya saja perbedaannya terletak pada bahan visual utama. Jika pada film, medium utamanya adalah video. Sementara audiophotography, medium utamanya adalah foto still. Sentuhan audio/sound pada karya fotografi akan memberi suasana cerita dan nuansa mood yang lebih hidup.
Secara teknis, mood akan dihasilkan melalui gabungan antara wild track dan transisi. Wild track itu bisa berupa sound effect, narrative audio, SFX, ambient, dan sebagainya. Sementara transisi dapat membantu pergerakan dari satu suara ke suara lain lebih halus (smooth). Transisi ini sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan dari suatu cerita.
Selain hal-hal teknis, seorang sound designer harus mampu mengenali karakter audio dari suatu lokasi. “Misalnya, bagaimana sih karakter dari suara aktivitas di pelabuhan antara Makassar dan Jakarta, kedua lokasi tersebut pasti memiliki perbedaan,” ujar Hafitz.
Menurutnya, ada karakter sound endemik atau suara asli yang hanya bisa didapatkan jika kita pergi ke lapangan untuk mengambilnya. Tetapi ada pula karakter sound yang generik, misalnya suara motor dan langkah kaki, yang bisa didapatkan dari bank audio di internet secara gratis.
“Waktu saya mengerjakan proyek foto tentang game itu, saya mengobrol dengan para gamers dan mencari tahu jenis game apa saja yang mereka mainkan. Saya mengambil audio dari suara-suara yang muncul di dalam game-nya. Saya memotong-motong audionya dan berpikir bagaimana caranya agar mendapatkan satu komposisi dan bisa in line dengan photo sequence yang sudah dibentuk,” cerita Hafitz saat mengingat-ingat proses kreatif yang pernah dilakukan.
“Apakah ada kesulitan ketika mengerjakan karya sendiri? Karena karya yang dibuat Hafitz itu hanya ada 10 frame, durasinya sangat pendek,” tanya Rifkianto Nugroho di sela-sela diskusi.
Hafitz bercerita bahwa itulah kesulitan yang pertama kali ia temui. Ia harus menyiasati agar durasi audio/sound yang masuk bisa sejalan dan seirama dengan durasi perpindahan setiap foto still. Akhirnya ia bisa mengatasi hambatan tersebut. Hafitz menambahkan visual effect pada fotonya sehingga bisa sedikit mempengaruhi panjang durasi.
“Cara mengakali tampilan satu frame agar durasinya tampak panjang, berarti harus ada pergerakan. Tipis-tipis saja, tak perlu terlalu banyak efek. Misalnya bisa dengan memanfaatkan efek zoom-in dan zoom-out atau dari terang ke gelap,” terang Hafitz.
Meski hari ini merupakan pertemuan terakhir dari pelatihan fotografi program PPG 2020, masih ada hal-hal lain yang belum tuntas dan perlu dikerjakan peserta. Mereka mulai menggarap presentasi karya multimedia untuk pameran foto daring. Selain itu juga mempersiapkan diri untuk acara graduation PPG 2020 yang akan dilaksanakan bulan depan. // Rizka Khaerunnisa
Hari Ketiga Final Editing bersama Jenny Smets

Jumat, (05/02/2021), merupakan sesi terakhir workshop intensif bersama Jenny Smets, kurator dan editor foto independen dari Belanda. Mekanisme editing masih sama seperti kelas-kelas sebelumnya. Mula-mula peserta menceritakan isi karyanya sambil menayangkan enam puluh foto all selected, lalu menampilkan dua puluh foto pilihan, dilanjutkan dengan memilih dua belas foto sequence versi awal, hingga memutuskan dua belas foto final sequence.
Kini giliran tiga peserta terakhir yang belum mempresentasikan karya. Ketiganya adalah Andri Widiyanto (Media Indonesia, Jakarta) dan Abriansyah Liberto (Tribun Sumsel, Palembang) yang membuat cerita reportase, serta Thoudy Badai Rifanbillah (Republika, Jakarta) yang membuat cerita personal.
Proyek foto yang digarap oleh Andri bercerita tentang seorang anak bernama Sandi yang terancam tak memiliki masa depan karena tidak memiliki akta kelahiran. Dampaknya ia tak bisa merasakan bangku sekolah formal. Bahkan, hanya karena tak punya identitas, ia tak memperoleh penanganan serius saat mengalami insiden kecelakaan yang menyebabkan kakinya pincang permanen. Ditambah keluarganya hidup dalam kemiskinan struktural khas pinggiran kota.
“Saya sangat suka cerita ini, Andri. Anda seolah-olah merasa dekat dengan anak ini, Anda juga bisa paham apa yang tengah terjadi padanya,” tutur Jenny setelah melewati proses diskusi yang cukup alot untuk menyusun dua belas foto sequence.
Sementara itu, cerita reportase yang dibuat oleh Liberto menyoroti kisah seorang guru bernama Siti Komariah yang tetap bertahan mengabdikan dirinya di sebuah sekolah dasar di desa Saluran, sebuah desa berjarak 20 Km dari pusat kota Palembang.
Di tengah keterbatasan fasilitas dan akses jalan menuju sekolah yang buruk, Siti Komariah tak menyerah. Meski hanya mengajar seorang diri, ia tetap setia mendidik siswa dari kelas 1 s.d. 6 yang berjumlah 20 orang. Siti Komariah bukanlah tamatan pendidikan tinggi dan hanya mengajar seorang diri. Upahnya hanya Rp 500.000 per bulan sehingga ia harus melakukan pekerjaan sampingan sebagai petani.
“Kenapa Anda memilih foto hitam-putih dan bukan yang berwarna? Kenapa ini penting?” Tanya Jenny.
Menurut Liberto, ia hendak menonjolkan sisi dramatis pada fotonya. Di desa tersebut, kondisi sumber listrik untuk penerangan tak memadai. Kondisi itulah yang pada akhirnya ia representasikan dalam karyanya dengan memainkan sentuhan kontras cahaya, antara terang dan gelap khas foto hitam-putih.
Terakhir, ada Thoudy yang menampilkan cerita personal dan konseptual. Ia memilih mood warna yang cenderung sendu serta sentuhan efek saturasi dan blurring sebagai representasi dari mimpi dan angan-angan atas ketiadaan sosok ayah dalam hidupnya.
“Cerita foto ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Saya tidak mengenali Anda secara personal, tetapi melalui foto-foto ini Anda berhasil membuat cerita yang bisa dipahami oleh semua orang. Ada tersirat perasaan melankolis dan sedih. Rasa kehilangan terhadap Ayah Anda sangat kuat di dalam foto ini. Karena cerita ini sangat pribadi dan berangkat dari perasaan personal Anda, cukup sulit untuk mengurutkan sequence-nya,” komentar Jenny sambil menelaah foto-foto yang ditampilkan di layar.
Di akhir sesi kelas, Jenny mengungkapkan suka-dukanya melewati tantangan photo editing di tengah kondisi pandemi. “Tidak selalu mudah untuk melakukan ini dari jarak jauh. Jauh lebih nyaman jika bisa bekerja bersama-sama secara langsung. Jika kita bisa bertemu secara fisik, foto yang dicetak bisa dijejerkan di atas meja sehingga proses editing akan lebih mudah,” aku Jenny.
Jenny serta para mentor lainnya memuji hasil akhir proyek foto yang digarap peserta selama dua bulan ini. Hasilnya di luar ekspektasi meski terjebak di tengah keterbatasan situasi.
“Mungkin karena saat ini pandemi dan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, teman-teman peserta jadi punya kesempatan untuk berkontemplasi dan berdialog dengan diri sendiri lewat karyanya. Level story yang dihasilkan teman-teman sungguh di luar dugaan,” puji Ng Swan Ti sambil tersenyum. // Rizka Khaerunnisa
Hari Kedua Final Editing bersama Jenny Smets

Workshop intensif bersama Jenny Smets, kurator dan editor foto independen dari Belanda, kembali dilanjutkan, Selasa, (02/02/2021). Sama seperti pekan lalu, setiap peserta membuka sesi editing dengan menceritakan isi karyanya sambil menayangkan enam puluh foto terpilih dari 4 sesi Photo Editing. Kemudian dilanjutkan dengan dengan menampilkan dua puluh foto pilihan, lalu dipilih lagi menjadi dua belas foto untuk kemudian dirangkai menjadi final sequence.
Pada pertemuan kedua ini, ada empat karya yang ditelaah. Keempat karya itu dibuat oleh Suci Rahayu (Kompas.com, Malang), Johannes P. Christo (Pewarta Foto Lepas, Denpasar), Nita Dian Afianti (Tempo, Jakarta), dan Nopri Ismi (Mongabay Indonesia, Kab. Bangka Tengah).
Keempat karya memiliki pendekatan storytelling yang berbeda-beda, mood visual yang bermacam-macam, serta gaya dan teknik yang beragam. Dalam hal pemilihan warna foto misalnya, ada yang memilih foto berwarna seperti pada karya Suci dan Nita serta ada pula yang memilih foto hitam-putih seperti pada karya Christo dan Nopri.
Meski sama-sama foto berwarna, ada perbedaan signifikan pada karya yang dibuat Suci dan Nita. Suci misalnya, ia memainkan warna-warna yang menimbulkan rasa gloomy dan sendu dalam setiap potretnya. Tak heran, sebab rasa-rasa seperti itu cocok dengan cerita yang ingin ia angkat. Kisah di dalam fotonya sangat personal, ada semacam ruang dialog dengan dirinya sendiri. Ruang dialog itu adalah proses healing yang tengah ia hadapi atas situasi perpisahan dengan pasangan sekaligus memaknai kembali hubungan dengan orangtua dan anak-anaknya, sementara di sisi lain harus tetap bertahan dalam kondisi pandemi yang serba tidak pasti.
“Ini cerita yang sangat bagus. Foto-foto ini menggugah efek dan mood tertentu di dalam diri saya. Apalagi terkait dengan situasi pandemi yang membuat kita terkurung di dalam rumah. Namun pada saat yang sama, saya masih bisa merasakan harapan yang muncul di dalam foto ini,” komentar Jenny saat mencermati satu demi satu foto karya Suci.
Sementara itu, Nita memilih eksperimen dengan sentuhan warna-warna cerah, seperti kuning, merah muda, dan putih. Namun warna cerah tak serta merta mengindikasikan isi cerita yang gembira. Sebaliknya, cerita yang dimunculkan Nita cukup kelam, yaitu tentang seorang penyintas kekerasan seksual di halte Harmoni Transjakarta pada 2014 silam. Dalam konteks ini, warna-warna cerah direpresentasikan sebagai harapan dan kekuatan seorang penyintas yang berupaya merebut kembali hak dan kendali atas hidupnya.
“Cerita ini adalah contoh yang bagus tetapi cukup sulit disusun menjadi sebuah sequence ya, sebab kita harus mempertimbangkan banyak elemen. Selain pertimbangan unsur cerita dan warna, Anda juga harus mempertimbangkan antara foto yang tajam dan yang halus. Selain itu, di sini juga banyak foto yang simbolis, jadi kita harus berhati-hati menyeleksinya,” kata Jenny mengungkapkan kesulitannya saat melakukan proses editing.
Selanjutnya beralih ke foto cerita hitam-putih pada karya Christo dan Nopri. Christo membuat cerita dengan langgam serupa dokumenter sementara Nopri cenderung bersifat reportase.
“Apakah ada alasan khusus kenapa memilih warna hitam-putih?” tanya Jenny kepada Christo.
Christo menjelaskan bahwa pemilihan warna hitam-putih merujuk pada efek tertentu yang bisa menonjolkan sifat keliaran pada subjek foto, sehingga ia sengaja mengeliminasi warna-warna yang mengganggu. Sebagai informasi, proyek foto yang dibuat Christo bercerita tentang anjing-anjing di Bali yang dilepas-liarkan oleh pemiliknya dan hal tersebut telah menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat Bali.
Selain Christo, ada Nopri yang mengangkat cerita reportase tentang komunitas suku laut Sekak di pulau Bangka. Imbas kebijakan pemerintah yang pernah dibuat pada era Soeharto membuat kehidupan suku laut berpindah ke daratan. Kini keberadaan mereka semakin terdesak akibat adanya aktivitas industri pertambangan timah serta problem regenerasi budaya dan kepercayaan lokal yang pelan-pelan mengikis.
Setelah mencermati foto-foto karya Nopri, Jenny mengungkapkan kesan bahwa ia seolah-olah mengenali karakter dan gaya tertentu yang acapkali diadopsi oleh banyak fotografer dokumenter. Ada permainan cahaya terang-gelap, efek blur, dan hitam-putih yang dramatis.
“Saya melihat kombinasi beberapa gaya fotografer dalam cerita ini dan itu sebetulnya bukan masalah besar. Namun jangan lupa, Anda juga harus mempertimbangkan bahwa orang-orang perlu mengenali karakteristik yang khas pada diri Anda, yang membedakannya dari fotografer-fotografer lain. Jadi harus berhati-hati saat mengadopsi gaya tertentu,” tutur Jenny memberi catatan. // Rizka Khaerunnisa
Hari Pertama Final Editing bersama Jenny Smets

Rangkaian progam Permata Photojournalist Grant (PPG) 2020 hampir mendekati proses akhir. Namun sebelum itu, peserta PPG harus melewati workshop intensif bersama Jenny Smets, kurator dan editor foto independen dari Belanda. Dalam sesi khusus ini, proyek foto masing-masing peserta akan ditinjau dan disusun ulang hingga menghasilkan final editing.
Kelas dibagi menjadi tiga kali pertemuan. Pada hari Jumat, (29/01/2021), ada tiga peserta yang mengikuti sesi khusus bersama Jenny ini, yaitu Indra Abriyanto (Harian Rakyat Sulsel, Makassar), Fanny Kusumawardhani (Fotografer Lepas, Jakarta), dan Rifkianto Nugroho (Detikcom, Bekasi).
Setiap peserta nantinya mendapat kesempatan sekitar satu jam untuk berdiksusi bersama Jenny dan mentor lainnya, mulai dari mempresentasikan karya, menampilkan enam puluh foto terpilih, mengeliminasinya menjadi dua puluh foto, hingga menyisihkan dua belas foto yang diurutkan dengan metode sequencing.
“Setiap kali melakukan proses editing, saya selalu ingin melihat all take-nya sehingga saya bisa membaca pendekatan yang dipilih oleh fotografer. Yang paling penting bagi saya sebagai editor, adalah melihat dan memahami suatu cerita tanpa harus ada yang bercerita secara harfiah kepada saya. Jadi, jika semua visual yang diperlukan ada dan lengkap, kita bisa melihat itu semua,” papar Jenny saat memulai sesi.
Menurut Jenny, untuk membangun photo story yang bagus, kita harus menyiapkan berbagai stok foto, tidak hanya yang memperlihatkan isi cerita tetapi juga yang bisa menentukan ritme dalam cerita. Misalnya, foto yang direkam dengan jarak pandang dekat maupun jauh (overview), foto yang bisa mengenalkan lokasi cerita, atau foto portrait dari orang-orang yang terlibat di dalam cerita. Sehingga, saat proses editing kita tidak kekurangan bahan cerita.
“Indra, dari editing yang sudah Anda kerjakan, foto mana yang paling penting bagi Anda? Foto mana yang bisa menceritakan seutuhnya dan mungkin bisa menjadi pembuka cerita?” Tanya Jenny kepada peserta pertama, Indra Abriyanto, sambil mempelajari berbagai macam foto.
Jenny selalu bertanya dan berdiskusi dengan para peserta tentang foto apa yang cocok dijadikan sebagai pembuka, kemudian bergerak alur demi alur, sampai pada penutup cerita dan mengapa foto-foto tersebut pantas dipertahankan.
“Bagi saya editing yang bagus itu adalah kombinasi yang mencakup dari berbagai aspek. Tidak hanya memmpertimbangkan foto dari segi konten, tapi juga foto-foto mana yang paling menarik bagi orang yang sedang melihat,” tutur Jenny.
Yang menarik dalam kelas kali ini, ketiga peserta menyajikan cerita dengan pendekatan, mood visual, dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Proyek foto yang dikerjakan Indra, misalnya, bercerita tentang seorang penyintas Covid-19 yang mengalami stigma dari tetangga di sekitar rumahnya. Menurut Jenny, foto-foto dari proyek ini terasa gelap dan gloomy. Ia memberi peringatan bahwa kita harus berhati-hati ketika menyusun urutan foto, jangan sampai kesan cerita yang dihasilkan terlalu berat dan kelam.
Selain Indra, cerita reportase juga dibuat oleh Rifkianto Nugroho. Cerita Rifki berfokus pada masalah body shaming dan standar kecantikan perempuan. Tokoh utamanya adalah seorang binaragawati yang mengalami body shaming, entah itu ketika kondisi tubuhnya masih gemuk maupun setelah melakukan aktivitas olah otot dan diet ketat.
Proyek foto yang dibuat Rifki cukup sulit untuk dibentuk dan disusun menurut Jenny. Ada banyak bahan, lokasi, dan komponen yang menarik. Namun pada saat yang sama, hal itu jadi sulit untuk menentukan dan memilih mana foto yang penting dan mana yang perlu dikeluarkan dari sequence.
Lalu, ada Fanny Kusumawardhani yang menyajikan cerita dengan pendekatan personal. Berbeda dengan Indra dan Rifki, foto cerita yang dibuat Fanny sifatnya konseptual. Ia membuat foto dari pantulan gambar yang diproyeksikan di dinding tempat tinggalnya yang sekarang. Subjek dalam foto yang dibuat Fanny adalah anggota keluarganya yang terpisah jauh akibat situasi pandemi Covid-19. Proyeksi itu menciptakan kesan yang seolah-olah nyata, padahal mereka tidak hadir secara fisik bersama Fanny.
“Perbedaan yang sangat besar dari cerita ini dengan cerita sebelumnya adalah karena foto-fotonya agak mirip. Jika Anda biasanya membuat photo story dengan narasi yang memiliki alur awal sampai akhir, kali ini tidak ada. Untuk mengurutkannya, kita harus melihat komposisi serta warna, dan bukan isinya. Sebab proyek ini konsepnya sama, formatnya sama, warnanya juga hampir sama. Jadi, kita harus mempertimbangkan ritme,” jelas Jenny menanggapi cerita yang ditampilkan Fanny.
“Bagaimana pendapatmu melihat hasil karyamu yang sekarang?” tanya Ng Swan Ti di sela-sela diskusi. Fanny mengungkapkan bahwa proyek ini cukup menantang bagi dirinya karena harus keluar dari zona nyaman dan mulai berani bercerita tentang dirinya sendiri.
Di akhir sesi, Jenny mewanti-wanti bahwa tidak ada editing foto yang paling benar dan selalu ada alternatif yang beragam. Fotografer juga harus punya pertimbangan apabila ingin mengeliminasi satu foto dan menggantinya dengan foto yang lain. Mengganti urutan foto berarti akan mengubah isi dari cerita yang ingin disampaikan.
“Pesan saya, jika nanti Anda mengubah editing yang sudah dikerjakan ini, lakukanlah dengan sadar sebab cerita Anda bisa berubah,” kata Jenny. // Rizka Khaerunnisa
Photo Editing 4: Mematangkan Konsep Photo Sequencing

Selasa, (26/01/2021), pelatihan fotografi, rangkaian program Permata Photojournalist Grant (PPG) 2020 kembali dilaksanakan. Pertemuan kali ini merupakan sesi editing terakhir bersama para mentor PannaFoto Institute sekaligus langkah awal menuju sesi editing yang lebih intensif bersama Jenny Smets, kurator independen dan editor foto, yang rencananya akan berlangsung mulai hari Jumat (28/01).
Teknis dan proses pada kelas editing keempat ini tak jauh berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Peserta masih dibagi menjadi dua kelompok dalam breakout room yang dibimbing oleh mentor Rosa Panggabean dan Yoppy Pieter. Masing-masing kelompok diberi waktu dua jam lima belas menit untuk melakukan proses editing. Yang membedakan, pada pertemuan ini lebih fokus untuk menyusun dan merapikan dua belas photo sequencing yang materinya telah disampaikan dalam kelas editing ketiga pekan lalu.
Setelah breakout room selesai, seluruh peserta dan mentor bergabung kembali dalam satu room bersama. Di sini setiap peserta melakukan latihan presentasi singkat sambil menampilkan dua belas foto cerita yang telah terpilih. Beberapa koreksi dan komentar pun dilontarkan oleh para mentor. Mereka memberi kritik dan saran agar peserta pandai-pandai memilih kalimat yang diutarakan ketika presentasi.
“Para peserta harus melatih kembali cara berbicara dalam membawakan presentasinya. Peserta harus ‘bercerita’ supaya lebih menarik, bukan menjelaskan,” Ujar Edy Purnomo.
Perjalanan peserta PPG 2020 dalam menyusun proyek foto cerita hampir mendekati tahap akhir, tinggal mematangkan editing dan memikirkan konsep pameran dan multimedia.
Di akhir pertemuan ini, para mentor meminta para peserta membagikan kesannya selama mengikuti rangkaian kelas PPG 2020, terutama dalam kelas editing.
“Ini kan kita sudah hampir mendekati proses akhir dan setelah ini editing bersama Jenny. Saya ingin tahu pendapat kawan-kawan, dari seluruh proses editing di PPG ini, kira-kira apa yang kawan-kawan dapatkan?” Tanya Edy Purnomo.
Nopri Ismi, pewarta foto Mongabay Indonesia, mengungkapkan bahwa dengan adanya kelas ini ia jadi terpicu untuk membuat cerita visual yang lain. Menurutnya, di kelas PPG, peserta diberi kebebasan dalam membangun cerita visual dan pengalaman ini berbeda jika dibandingkan ketika bekerja di industri media.
“Kebebasan, dalam artian apa yang ingin kita bentuk atau apa yang ingin kita sampaikan, mentor juga memiliki satu pengertian yang sama. Jadi lebih nyambung dan enak,” tambah Nopri.
Selain Nopri, ada Thoudy Badai Rifanbillah, pewarta foto Republika, yang turut membagikan kesannya terkait pengalaman mengikuti rangkaian program PPG ini.
“Kalau aku, sih, jadi banyak ilmu yang didapatkan, meskipun online. Mungkin hambatannya datang dari pribadi, ada perbedaan antara ngobrol secara online dan offline. Kalau offline, kan, kadang-kadang ada pertanyaan yang lahir dari obrolan biasa, sementara komunikasi lewat online rasanya masih agak kaku. Tapi, untuk materi-materi yang didapatkan sangat membuka mata, sih, bagaimana cara-cara bertutur lewat visual,” ujar Thoudy.
Johannes P. Christo, Pewarta Foto Lepas dari Denpasar, mengaku bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah diketahui tetapi ia tinggalkan dan tak dieksplorasi lebih jauh.
“Akhirnya, di PPG ini banyak hal baru yang tentunya akan menjadi bahan dan landasan saya dalam berkarya ke depannya,” tutur Johannes.
Sebagai penutup pertemuan, Ng Swan Ti, Managing Director PannaFoto Institute, mewanti-wanti agar peserta tak berhenti berlatih dan berkarya setelah program PPG ini rampung. Peserta yang sudah intensif menempuh kelas PPG selama tiga bulan tidaklah otomatis menjadikan dirinya fotografer yang hebat. Tanpa latihan, ilmu yang didapatkan akan sia-sia. Dengan berlatih secara mandiri, Swan Ti berharap, kemampuan peserta PPG sudah naik level jika suatu hari nanti muncul peluang baru yang bisa menunjang impian maupun karier.
“Jadi, PPG ini sebetulnya bukan akhir, justru merupakan awal perjalanan untuk mengembangkan kemampuan kalian,” kata Swan Ti. // Rizka Khaerunnisa
Riset Audiens dan Presentasi Photo Story bersama Saša Kralj

“Apakah kita telah menemukan relevansi pada cerita foto yang kita kerjakan?” Saša Kralj, founder Živi Atelje DK, Zagreb, mengajukan pertanyaan pembuka tersebut dalam pelatihan fotografi, rangkaian program Permata Photojournalist Grant (PPG) 2020, Jumat, (22/1/2021).
Relevansi yang dimaksud yaitu, apakah cerita kita bisa relevan terhadap diri kita sendiri, apakah relevan terhadap protagonis di dalam cerita, dan apakah relevan terhadap audiens. Jangan sampai kita terlalu fokus pada diri sendiri dan tidak peduli dengan target audiens yang ingin dicapai.
Menentukan target audiens barangkali jadi problem bagi kebanyakan fotografer karena ada kecenderungan ingin memuaskan semua orang. Namun yang kerap terjadi justru fotografer terjebak pada cerita yang terlalu umum dan dangkal sehingga hasil akhirnya tidak memuaskan siapapun. Inilah mengapa riset audiens menjadi hal yang sangat penting.
“Jadi kita harus membayangkan audiens kita, bagaimana audiens akan bereaksi terhadap cerita kita. Jangan membuat cerita hanya karena itu menarik bagi Anda saja,” ujar Saša.
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu jika cerita tersebut relevan terhadap audiens atau tidak?
Menurut Saša, langkah paling awal yaitu kita harus mampu mendefinisikan audiens kita terlebih dahulu. Kita harus memiliki bayangan dan tahu cara mengkomunikasikan cerita kepada audiens dengan kritis. Saša menekankan, jangan sampai kita terkesan menggurui audiens dan berasumsi bahwa mereka tidak tahu apa-apa.
Selanjutnya, hal yang harus dipikirkan oleh fotografer adalah jenis penyajian karya seperti apa yang akan dipilih. Fotografer sering berpikir bahwa foto saja sudah cukup, namun melalui foto esai kita juga bisa mengumpulkan teks demi teks. Maka, jika kita ingin menampilkan karya pada halaman koran, pilihan penyajiannya adalah gabungan foto dengan caption pendek.
Namun, di era digital seperti sekarang, penyajian karya dengan hanya menampilkan foto dan teks saja tidaklah cukup. Fotografer harus kreatif dan berani tampil berbeda mengemas karyanya. Caranya yaitu dengan memanfaatkan multimedia sebagai pelengkap medium cerita.
Multimedia berarti “semuanya”. Semua yang bisa digunakan sebagai medium cerita. Misalnya, di samping foto sebagai karya utama, kita bisa menambahkan sound effect, musik, video, lukisan atau gambar, bahkan patung.
“Saya ingin menunjukkan bahwa fotografi itu jangan dijadikan sebagai penjara. Storytelling adalah suatu ruang yang terbuka, bebas kita jelajahi,” tutur Saša.
Saša memperlihatkan contoh proyek foto close up portrait orang-orang tunawisma berjudul to Ronto (2011) yang direkam oleh Delibor Talajic. Saat karya tersebut digarap, sang fotografer hanya mengikuti workshop pendek di Toronto, Kanada, sehingga tidak sempat melakukan banyak riset. Akhirnya ia menambahkan lapisan emosional dari proyek tersebut dengan efek suara. Hasilnya punya efek berbeda jika dibandingkan dengan tampilan foto still saja.
“Seandainya ada foto yang cerita dan visualnya kurang kuat, apakah itu bisa diperkuat dengan presentasi? Atau justru sebaliknya, visualnya dulu yang harus kuat baru kemudian presentasi multimedia bisa mengikuti untuk menambah target audiens?” Tanya Johannes P. Christo, salah satu peserta PPG 2020 yang juga merupakan pewarta foto lepas dari Denpasar.
Menurut Saša, jika visual cerita itu entah kuat atau tidak kuat, sebetulnya tiap elemen memiliki kekuatannya masing-masing. Misalnya elemen musik, kekuatannya adalah untuk memicu memori karena dari setiap suara yang didengar kita akan mendapatkan kilasan-kilasan ingatan yang pernah terjadi sebelumnya. Lain hal lagi soal elemen visual, ia memiliki ketertarikan simfoni yang muncul dalam satu waktu lewat gambar still. Lalu, elemen teks memiliki kekuatan informasi yang terkandung di dalamnya. Sementara kekuatan dari elemen efek suara adalah memberi nuansa emosi, misalkan suara-suara tertentu yang menimbulkan kesan tegang dan drama.
Oleh sebab itu, peran riset audiens menjadi penting sebab kita ingin berinteraksi dengan audiens secara emosional dan penyajian karya dalam bentuk multimedia menyediakan keluasan dan kebebasan eksplorasi.
Pameran di dalam ruang tiga dimensi tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan presentasi di dalam buku foto (dua dimensi). Setiap ruang, setiap medium, dan setiap audiens membutuhkan cara dan perlakuan yang berbeda-beda.
“Pada masa sekarang, eksplorasi penggunaan multimedia semakin luas, batasan-batasan lama sudah tidak ada lagi. Bahkan, pameran saat ini jauh lebih berani, tidak melulu menggantungkan foto-foto di dinding dalam ukuran yang sama, presentasi semacam ini agak membosankan,” jelas Saša. // Rizka Khaerunnisa
Mengulas dan Menyunting Tulisan untuk Esai Foto

“Belajar menulis itu sama seperti orang belajar naik sepeda,” kata Budi Setiyono, wartawan dan Redaktur Pelaksana Historia.id, mengawali kelas penulisan narasi sesi dua sambil menunjukkan ilustrasi orang yang tengah belajar naik sepeda di layar zoom meeting, Selasa, (19/1/2021). Jika pada sesi pertama para peserta mendapatkan pengetahuan seputar teori menulis, kali ini tulisan yang telah mereka kerjakan selama satu minggu diulas satu per satu oleh mentor tamu tersebut.
Budi mengumpamakan bahwa belajar menulis sama seperti belajar naik sepeda. Satu-satunya cara paling tepat adalah mencoba. Mungkin kita bisa memperoleh penjelasan langkah-langkah naik sepeda di YouTube, namun hal itu akan menjadi percuma jika tidak dibarengi dengan praktik secara langsung.
Dalam prosesnya, kita akan terjatuh, lalu bangkit dan mencoba lagi, dan seterusnya. Di samping itu, kita juga butuh dorongan dari orang yang lebih berpengalaman. Kalau dalam proses penulisan, kita akan membutuhkan seorang teman yang sudah terlatih dalam menulis atau seorang editor untuk mendorong kita agar terus maju dan mencoba.
“Teori itu sebetulnya hanya dipakai sekian persen saja. Dalam menulis yang lebih penting itu praktiknya. Kalau kita selalu mengingat-ingat kembali teorinya, justru hal itu akan membelenggu kita, membuat kita tidak merasa lepas ketika menulis,” tambah Budi.
Aturan dasar dalam menulis hanya ada dua, yaitu membaca dan menulis. Jika tidak pernah membaca, kita tidak akan mendapatkan topik-topik yang menarik dan tidak bisa memperdalam tulisan yang dibuat. Oleh sebab itu, selain memperoleh perspektif baru, dengan membaca kita juga akan tahu bagaimana cara menyusun kalimat dan memilih kata. Setelah kebiasaan membaca terbentuk, maka dorongan untuk menulis pun akan muncul.
“Kalau di kalangan wartawan atau penulis itu kan ada istilah ‘banyak tahu meskipun sedikit’. Jadi bacaan apa saja saya lahap,” tutur Budi.
Menulis merupakan proses yang panjang. Bahkan Budi mengakui, ia menganggap dirinya masih dalam tahap belajar menulis. Proses menulis itu selalu berkembang. Jika hari ini kita membaca ulang tulisan beberapa tahun lampau, perspektif dalam tulisan tersebut niscaya akan usang dan berbeda.
Sepanjang proses penulisan, kita jangan sampai melupakan aspek lain yang tak kalah penting yaitu kegiatan menyunting. Budi mewanti-wanti, penulis yang baik pada hakikatnya selalu menjadi editor yang baik bagi dirinya sendiri.
Selama kurang lebih tiga jam kelas berlangsung, Budi membedah satu per satu naskah yang sudah dikerjakan oleh para peserta. Peserta diminta untuk membacakan tulisannya dan dilanjutkan dengan proses penyuntingan. Secara umum, kekeliruan bahasa yang kerap dijumpai yaitu, salah tik, penggunaan tanda baca yang kurang tepat, Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang belum diterapkan, pilihan kata yang kurang akurat, hingga logika kalimat yang rancu.
Dalam setiap sesi penyuntingan, peserta mengutarakan tentang kesulitan-kesulitan saat proses menulis. Salah satunya Nita Dian Afianti, pewarta foto Tempo, yang akan kesulitan menulis jika tidak menemukan poin-poin penting untuk paragraf pembuka penutup. Sebagai informasi, poin paragraf pembuka lazim disebut lead. Sejatinya, lead yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menuntaskan cerita dari awal sampai akhir.
“Aku itu tipe orang yang kalau nulis harus tahu depannya. Jadi selama depan dan akhir tulisannya belum ketahuan, biasanya cerita akan melebar ke mana-mana. Kalau sudah tahu, biasanya lebih lancar menulis,” kata Nita.
Perihal ini, Budi juga mengingatkan tentang pentingnya membuat kerangka dan struktur cerita terlebih dahulu. Tujuannya agar ide-ide yang acak bisa tersusun rapi dan tidak menyulitkan kita ketika menulis. // Rizka Khaerunnisa
Photo Editing 3: Menyusun Cerita Foto dengan Metode Sequencing

Jumat, (15/1/2021), pelatihan fotografi, rangkaian program Permata Photojournalist Grant (PPG) 2020 memasuki sesi kedelapan. Kelas dibagi menjadi dua babak. Pada babak pertama, peserta dipecah menjadi dua kelompok kecil. Masing-masing kelompok dibimbing oleh mentor Rosa Panggabean dan Yoppy Pieter. Bersama para mentor, setiap peserta menyeleksi dan memilih 15 foto (minimal) dari empat puluh lima foto yang diajukan.
Pada babak kedua, seluruh peserta bergabung kembali dalam satu room. Di tahap ini, Edy Purnomo memaparkan materi tentang Photo Sequencing.
“Mengapa membuat sequencing di editing ketiga? Tujuannya agar peserta tahu, pertama kira-kira ceritanya mau dibawa ke mana. Kedua, bagaimana cara menyusun cerita itu. Terakhir, bagaimana menguatkan dan menambah yang kurang dari struktur yang ada,” terang Edy.
Secara garis besar metode sequencing terdiri dari tiga tahapan, yaitu clustering (pengelompokkan foto), menyusun, dan story arc.
Jika ingin mengedit foto, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengelompokkan foto-foto itu terlebih dahulu. Pengelompokkan foto mula-mula harus diseleksi berdasarkan mood visual yang ditampilkan. Tahapan ini harus memperhatikan kepaduan warna, angle, hingga visual approach (pendekatan visual) sekaligus bagaimana pendekatan visual itu digunakan.
“Jangan sampai belang secara mood visual karena hal ini akan mengganggu banget dalam proses editing nanti. Misalnya, kalau kebanyakan warna-warna [red: dalam fotonya] blues atau biru, tiba-tiba muncul satu foto yang warnanya putih sendiri. Itu kalau tidak diperlukan, ya tidak usah dipakai. Meskipun terkadang ada yang memakai itu,” ujar Edy.
Edy mengibaratkan ihwal mood visual ini sama seperti cara kita mendengarkan musik. Melodi dalam musik setidaknya harus selaras dan berirama. Ketika tiba-tiba muncul satu nada yang menyimpang, musik akan terdengar aneh di telinga. Begitu pula dengan cerita foto. Rangkaian dari satu foto menuju foto yang lain harus selaras.
“[Memang] secara teori, tak ada aturan baku. Tetapi, nanti ketika kita melihat visual secara keseluruhan, kita baru bisa merasakan bagaimana cerita punya flow, bagaimana satu foto dengan foto lainnya punya keterkaitan berdasarkan mood-nya. Konten pada akhirnya bisa mengikuti asalkan mood visual-nya sama.”
Setelah mood visual dapat ditangani secara baik, baru bisa menyeleksi foto berdasarkan konten atau isi cerita dan dilanjutkan dengan menyusun foto secara berurutan.
Agar susunan cerita foto padu dan utuh, diperlukan kerangka story arc. Setidaknya ada tiga bagian dalam story arc yang dimulai dengan exposition sebagai pembuka cerita. Kemudian cerita mulai bergerak sampai pada klimaks dan ditutup dengan resolution.
“Kunci dari editing [sebetulnya] teman-teman harus menanamkan di dalam kepala bahwa editing itu bukan kumpulan foto-foto bagus,” tambah Yoppy di sela-sela diskusi.
Meski pada akhirnya foto dituntut harus bagus, namun hakikat cerita foto tak sekadar demikian. Yang paling penting adalah keterkaitan antara satu frame ke frame berikutnya.
Yoppy juga mengatakan bahwa fotografer harus membuang jauh egonya saat masuk dalam proses editing.
“Saya bisa paham banget, misalnya ada fotografer bilang seperti ini, ‘foto ini harus masuk karena gue susah banget motretnya, gue harus manjat tebing, gue harus jatuh dari motor…’ Orang di luar sana tidak peduli dengan hal itu. Yang saya peduli adalah apakah foto ini nyambung dengan cerita dalam tatanan frame-frame yang kalian tampilkan. Jadi buang jauh-jauh ego itu,” jelas Yoppy lagi.
Di akhir sesi, para mentor meminta agar peserta menyusun pokok cerita, maksimal dalam 3 kalimat. Proses ini akan menentukan sejauh mana peserta menguasai inti cerita yang ingin diungkapkan kepada audiens. Jangan sampai cerita itu disampaikan dalam kalimat yang bertele-tele dan menyebabkan audiens gagal memahami arah cerita.
“Kalau itu tidak clear, saya yakin seratus persen teman-teman akan merasa kesulitan menyusun cerita. Apalagi kalau lebih dari tiga kalimat, teman-teman fotografer pasti akan kebingungan membuat sequencing-nya,” ujar Edy. // Rizka Khaerunnisa
Mengenal Dasar-Dasar Penulisan

Foto dan teks merupakan satu paket, melengkapi satu sama lain. Sebagai pewarta foto kedua hal ini menjadi kemampuan kunci yang harus dikuasai. Selain piawai menangkap momen menggunakan kamera, juga harus memiliki kemampuan untuk menuliskan hal-hal yang tidak dapat digambarkan dengan visual. Untuk itu, program Permata Photojournalist Grant selalu memasukkan materi penulisan ke dalam kurikulumnya. Program PPG 2020 mengundang Budi Setiyono (Redaktur Pelaksana Historia.id) untuk memberikan materi Penulisan 1 pada Selasa (12/01/2021).
Materi kelas berangkat dari penjelasan tentang bentuk-bentuk penulisan berita; Berita Lempang, Feature, dan Narasi. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk penulisan berita memberikan gambaran konten dan struktur tulisan yang akan dibuat. Misalnya dalam Berita Lempang atau Berita Langsung, cukup berisi informasi umum seperti Apa, Kapan, dan Dimana. Sementara untuk Feature dan Narasi, bisa memberikan informasi yang lebih mendalam.
Jika dalam sesi 5: Research For Documentary Photography, mentor pada sesi itu, Saša Kralj, menekankan pentingnya untuk melakukan riset berulang kali. Di pertemuan kali ini Budi menekankan hal yang sama, riset dan observasi penting dilakukan sebagai awal persiapan penulisan. Ia juga menyampaikan wawancara tidak cukup dilakukan satu kali, harus berulang kali selain untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari narasumber atau subyek foto, juga untuk lebih mengenal subyek foto atau narasumber.
Budi juga menyampaikan pentingnya untuk memelihara rasa ingin tahu dan skeptisme. Skeptisme artinya mempertanyakan banyak hal: Apakah sumbernya terpercaya? Apakah informasi yang didapat sudah benar?
"Penulis yang baik adalah juga editor yang baik. Kita harus membiasakan untuk menyunting tulisan kita sendiri. Pastikan tidak ada salah ketik, pastikan alur tulisan enak dibaca, jika kurang yakin mintalah orang lain untuk membaca tulisanmu," Budi berpesan.
Sunting tulisan secara mandiri menjadi salah satu bagian penting dalam penulisan. Tidak sedikit kasus penulis tidak membaca ulang tulisannya, sehingga banyak ditemukan salah tulis di sana-sini. Bahkan, ada yang lupa mencantumkan judul tulisan. // Lisna Dwi Astuti
Mendedah Makna Foto Lewat Visual Literacy
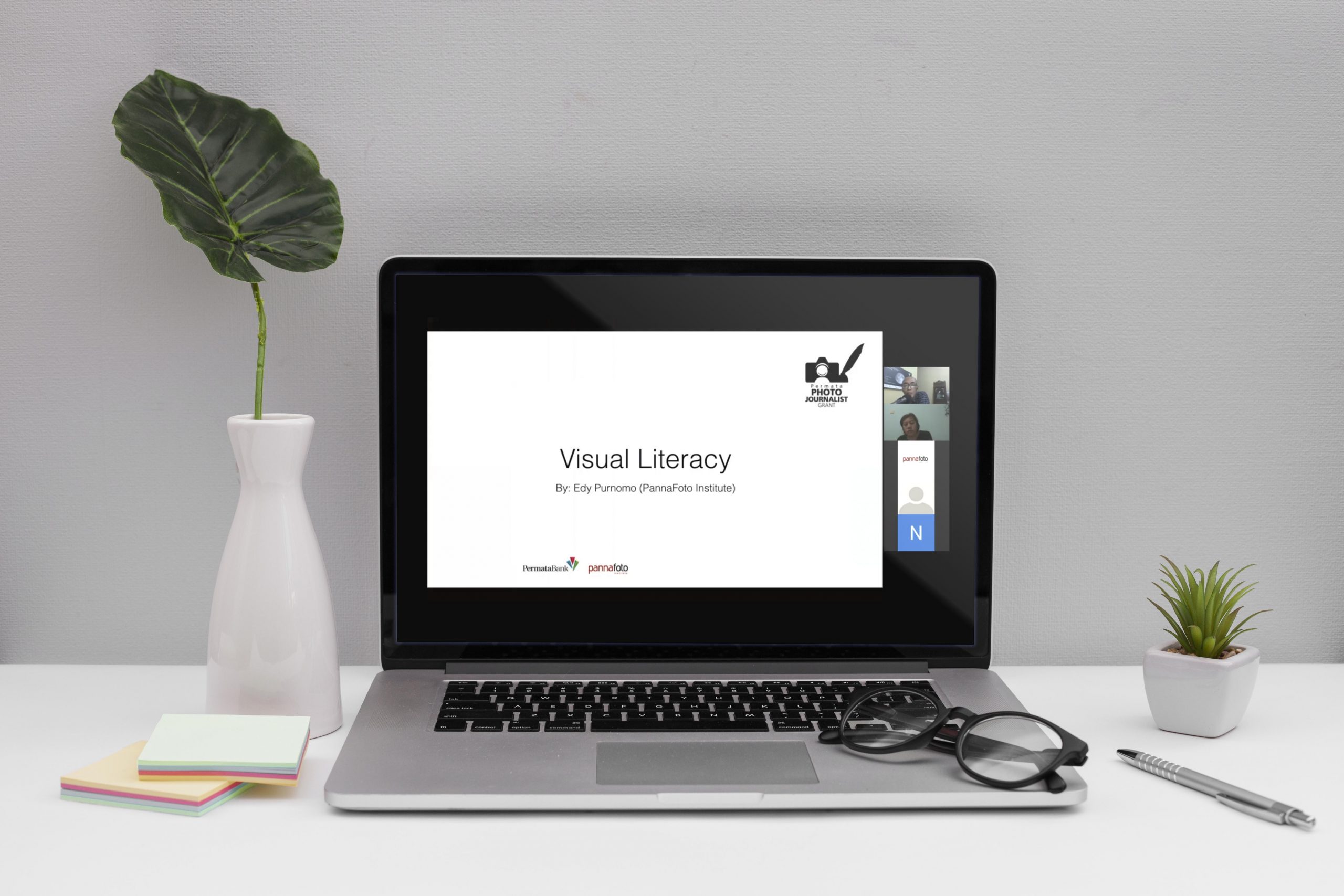
Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa pengetahuan visual tak benar-benar penting untuk dipelajari. Sejak lahir hingga dewasa, kita telah terbiasa menerima fungsi panca indera tanpa perlu dipertanyakan lagi. Sehingga muncullah anggapan bahwa kita bisa menangkap arti dan makna yang dilihat lewat mata hanya berdasarkan insting.
“Ini yang kadang pincang. Di Indonesia, Visual Literacy itu memang tidak dipelajari di sekolah-sekolah, dianggap ilmu ini tidak begitu penting. Padahal, kalau kita lihat di masa sekarang, kita hidup di era budaya visual. Coba hitung, berapa persen kita menggunakan visual dalam kehidupan sehari-hari?” Ujar Edy Purnomo, mentor PannaFoto Institute, dalam kelas daring ketujuh yang merupakan bagian dari Pelatihan Fotografi program Permata Photojournalist Grant (PPG) 2020, Jumat, (8/1/2021).
Setidaknya, Edy menyebutkan tiga poin yang perlu digarisbawahi kenapa Visual Literacy menjadi penting untuk dipelajari.
Pertama, seperti yang sudah dikatakan, sekarang kita hidup dalam era budaya visual. Apa yang kita produksi dan konsumsi, semuanya berbahasa visual. Apalagi didukung oleh media sosial, penyebaran informasi visual tentu jauh lebih cepat menyebar.
Disadari atau tidak, sesungguhnya informasi visual lebih memorable atau mudah lekat pada memori kita ketimbang informasi tekstual. Menurut Edy, 70 s.d. 85% informasi yang diserap manusia didapatkan lewat bahasa visual. Ditambah pada fakta dalam sepanjang hidupnya, manusia akan selalu mengingat memori-memori visual itu.
Kemudian poin kedua, wujud visual mempermudah cara manusia berkomunikasi. Dan yang ketiga, Visual Literacy dapat memperkaya pemahaman kita terhadap sesuatu.
Maka bagi para peserta PPG 2020 yang notabene fotografer, tak pelak bahwa pengetahuan Visual Literacy ini sangat membantu mereka untuk menggodok karya yang akan digarap.
Untuk memahami seperti apa cara membaca dan memaknai karya foto, Edy memaparkan perihal elemen-elemen visual dan teori Gestalt sebagai alat bantu membedah karya. Nantinya, bagi kreator, kedua pengetahuan itu sangat berguna untuk menciptakan imaji yang diinginkan. Sementara bagi pembaca/audiens/penikmat karya, hal tersebut memudahkan analisa seseorang ketika membangun sebuah persepsi.
“Terkadang Nopri baru sadar [red: ada] makna visual setelah memotret, apakah itu baik?” Tanya Nopri Ismi, pewarta foto Mongabay Indonesia, yang juga peserta PPG 2020.
Menurut Edy, sebetulnya harapan untuk peserta setelah mempelajari Visual Literacy ini adalah bisa membuat analisa terlebih dahulu sebelum memvisualkan ide yang ingin disampaikan. Analoginya sama seperti seseorang yang ingin membuat tulisan, setidaknya ia punya bekal teoretis dan tahu goals atau tujuan apa yang ingin dicapai. Jika seorang kreator tidak tahu cara membaca atau buta visual, pesan maupun maknanya jadi tak begitu jelas. Memang, karya itu kemungkinan besar masih bisa dibaca, tetapi tak seperti apa yang diharapkan.
Di sisi lain, Yoppy Pieter, fotografer dan Mentor PPG 2020, menambahkan bahwa sesungguhnya Visual Literacy lebih dari sekadar pre-visualisasi sebelum seseorang memotret. Dengan kemampuan Visual Literacy yang kaya, cara seseorang melihat subjek maupun objek sudah pasti berbeda.
“Jadi, mau di medan apapun, mau di kondisi apapun, ya kita sudah siap dan nggak takut lagi atau bingung mau memotret apa dan seperti apa,” ujarnya.
Pengetahuan tentang Visual Literacy pada akhirnya memegang peran vital saat mematangkan proses visualisasi, bahkan jauh sebelum karya itu diproduksi. Ia akan jadi stimulus di kepala seorang fotografer dan proses memotret pun jauh lebih mudah secara intuitif. // Rizka Khaerunnisa
Photo Editing 2: Tantangan Untuk Peserta Dalam Pengerjaan Proyeknya

Selamat tahun baru! Mengawali tahun baru 2021, 10 penerima Permata Photojournalist Grant (PPG) kembali bertemu dengan mentor Edy Purnomo, Rosa Panggabean, dan Yoppy Pieter pada Selasa (5/01/2021) untuk sesi VI Pelatihan Fotografi, dengan materi Photo Editing II.
Sama seperti Photo Editing I, kelas langsung dibagi ke dalam dua breaking room, kelompok Rosa dan kelompok Yoppy, masing-masing mengampu 5 peserta. Sebelumnya, masing-masing peserta telah mengirimkan 45 frame foto baru, dalam sesi ini peserta memiliki tugas untuk memilih 15 foto yang mereka anggap menarik. Lalu, bersama mentor mereka mendiskusikan foto-foto terlebih apakah kira-kira dapat digunakan dalam photo story mereka.
Usai sesi breaking room, seluruh peserta dan mentor kembali ke ruang utama untuk presentasi oleh peserta dan diskusi.
"Bagaimana menghadirkan yang tidak terlihat. Misal seperti di cerita tentang anjing oleh Christo [Johannes P. Christo - Pewarta Foto Lepas, Denpasar], bagaimana menghadirkan anjing tanpa gambar anjing secara literal. Ini adalah tantangannya," tutur Edy Purnomo dalam diskusi. Edy juga menyampaikan tantangan yang sama bagi Nopri Ismi (Mongabay Indonesia, Kab. Bangka Tengah) dan Abriansyah Liberto (Tribun Sumsel - Tribun Network, Palembang) untuk dapat menghadirkan subyek utama mereka dalam cerita tanpa gambar/foto sosok mereka secara literal, membuat audiens merasakan kehadiran subyeknya.
"Sama seperti konsep 'Harapan' yang abstrak juga," tambah Ng Swan Ti (Kepala Sekolah Program).
Hope atau Harapan dipilih menjadi tema program PPG 2020, tema ini rasanya tepat bagi situasi dan kondisi dunia yang saat ini berada di tengah pandemi. Kesepuluh peserta diharapkan dapat memberikan cerita-cerita yang menginspirasi dan memberikan pesan dan semangat bagi audiens yang menikmati karya-karya mereka nantinya. Tantangannya adalah bagaimana agar audiens dapat menangkap pesan ini dari melihat-melihat photo story mereka. Untuk mencapai itu, masih ada 9 sesi pertemuan yang harus diikuti oleh peserta untuk berproses dalam pelatihan ini dan menghasilkan karya-karya yang tidak hanya menarik tapi juga memiliki pesan yang kuat. // Lisna Dwi A.
Riset Proyek Fotografi Bersama Sasa Kralj

Saša Kralj, fotografer dan co-founder Živi Atelje DK di Zagreb, Kroasia. Saša telah menjadi bagian dari program Permata Photojournalist Grant sejak penyelenggaraan pertama PPG pada tahun 2011. Di tahun kesepuluh, sepuluh peserta PPG 2020 bertatap muka dengan Saša melalui layar laptop pada hari Jumat (22/12/2020) untuk mendengarkan penyampaian materi bertajuk Research For Documentary Photography.
Dalam sesi ini Saša memaparkan terdapat lima level penelitian dalam sebuah proyek fotografi yang harus dilakukan secara berkesinambungan, yakni descriptive level, representative level, intimate level, implication level, dan purpose level. Kelima level ini untuk memahami dan mengenal secara mendalam cerita dan subyek foto dari proyek fotografi yang sedang dikerjakan.
Setelah pemaparan singkat, Saša membagi peserta ke dalam beberapa grup untuk berdiskusi tentang pemahaman mereka atas materi yang baru saja disampaikan Saša terkait General Knowledge dan bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan itu di dalam Mind Map mereka masing-masing.
"Mind Map bukan lah berisi hal-hal yang kamu ketahui, melainkan tentang hal-hal yang memerlukan riset lebih lanjut. Jika Mind Map hanya berisi pemaparan hal-hal sudah kamu ketahui, berarti ceritamu bermasalah. Kalian harus selalu memiliki pertanyaan yang belum terjawab dalam Mind Map kalian," tutur Saša. Semakin banyak pertanyaan yang memerlukan jawaban, semakin besar riset yang perlu dilakukan, dengan demikian peserta diharapkan dapat semakin masuk dan memahami cerita mereka masing-masing.
Saša menekankan peserta bahwa riset tidak cukup dilakukan sekali saja, ia menawarkan siklus kerja dalam penyusunan proyek fotografi, dimulai dengan menemukan ide cerita yang akan diangkat - riset - memotret - edit (melihat dan memilah foto-foto yang sudah diambil) - kemudian riset lagi - memotret lagi - edit lagi - riset lagi dan begitu seterusnya. Dapat dikatakan, fotografer pun harus mampu mengkritisi foto-foto mereka, mempertanyakan diri seberapa mereka memahami permasalahan dalam cerita yang sedang mereka kerjakan. // Lisna Dwi A.












